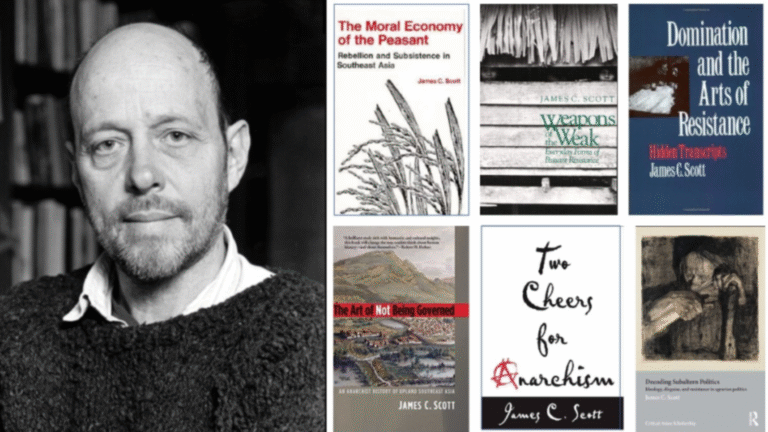Oleh: Dimas Saputra
Semarang, Justisia.com – Di brosur-brosur promosi dan sambutan hangat masa orientasi, kampus sering digambarkan sebagai tempat paling menyenangkan. Ruang aktualisasi, laboratorium ide, dan rumah tumbuhnya masa depan. Namun, tidak semua mahasiswa menapaki kampus dengan langkah penuh semangat. Sebagian dari mereka datang karena gagal, karena kalah di pilihan pertama, atau bahkan karena tidak tahu harus ke mana lagi.
Begitulah yang dirasakan oleh beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo yang tidak pernah benar-benar memimpikan kuliah di kampus ini, apalagi mencintainya.
Mereka Tidak Pernah Memilih, Mereka Didorong Masuk
Kampus ini bukan rumah bagi mimpi mereka. Dina mengaku, UIN tidak hanya bukan prioritas, tapi bukan bagian dari rencananya sama sekali.
“Kuliah di sini tuh kayak, bukan tujuan utama, lebih kayak opsi terakhir karena semua pilihan udah buntu,” katanya.
Senada dengan itu, Imam juga menyimpan kekecewaan sejak awal karena kampus impiannya tak bisa dia masuki.
“Beberapa kali saya daftar di PTN lain, gagal. UIN ini akhirnya jadi jalan yang tersisa, bukan pilihan yang saya perjuangkan sejak awal,” ucap Imam.
Ironisnya, bukan hanya kampus yang terasa asing. Jurusan yang mereka tempuh pun bukan berasal dari dorongan hati.
“Aku sebenarnya pengen keperawatan. Tapi karena di sini nggak ada, akhirnya ambil pendidikan,” ujar Manda yang saat ini ia mengambil jurusan PGMI.
“Dulu mikirnya pendidikan itu simpel, ternyata nggak juga,” tambah Manda.
Jurusan yang Tak Ramah, Sistem yang Tak Mengerti
Banyak dari mereka yang merasa tertipu oleh sistem akademik kampus. Imam, misalnya, mengira gelar yang nanti ia dapat sesuai dengan jurusannya. Tapi kenyataan berkata lain.
“Aku masuk ISAI, tapi ternyata prodi ini di bawah FUHUM dan yang lebih aneh, setelah lulus gelarnya tidak sesuai dengan jurusan yang aku ambil. Aku kecewa banget,” jelasnya.
Imam bukan satu-satunya yang merasa dicurangi oleh label dan struktur. Rani, yang awalnya tertarik hukum pidana Islam, justru ditertawakan lingkungan sosialnya.
“Katanya, jurusan kayak gitu kerjanya cuma di Aceh. Bahkan ada yang bilang, ‘ngapain kuliah hukum Islam, susah cari kerja.’ Padahal aku belajar sungguh-sungguh lho,” tutur Rani.
Mereka merasa tak hanya harus menghadapi materi kuliah yang berat dan tidak diminati, tapi juga beban sosial dari luar kampus yang mempertanyakan pilihan hidup mereka, padahal mereka sendiri pun tidak pernah benar-benar memilihnya.
“Aku Capek. Beneran Capek.”
Tiga tahun berjalan, banyak dari mereka hanya ingin cepat-cepat keluar. Bukan karena ingin mengejar dunia luar, tapi karena kampus tidak lagi berarti apa-apa.
“Yang aku rasakan selama kuliah tiga tahun ini? Capek. Pengen cepat tamat,” ujar Dina.
Ia merasa bahwa kampus ini terlalu formal, kaku, dan minim ruang eksplorasi diri. Semuanya berjalan seperti robot: jadwal, tugas, laporan. Tak ada momen yang bisa dikenang.
“Fun fact? Nggak ada. Kuliahnya datar, hidupnya formal. Nggak kayak cerita orang yang bilang kuliah itu masa emas,” katanya getir.
Rani juga mengalami kelelahan mental, bukan karena tugas, tapi karena beban relasi sosial di dalam kelas. Tugas kelompok yang seharusnya jadi momen kerja sama, justru penuh dengan ketidakadilan.
“Banyak yang cuma numpang nama. Gak ngerjain apa-apa tapi tetap dapat nilai. Dan yang paling nyebelin, mereka santai aja seolah itu normal,” katanya.
Realitas Sosial dan Retaknya Citra Mahasiswa UIN
Di luar tembok kampus, mahasiswa UIN juga tak lepas dari stigma. Bahwa mereka pasti religius, tahu agama luar dalam, sopan, dan siap jadi guru agama.
Manda juga sempat kaget karena realita di lapangan tak seperti gambaran umumnya.
“Aku pikir anak UIN itu pasti alim-alim semua. Ternyata? Banyak yang biasa aja. Ada yang bebas banget. UIN nggak se-islami itu kok, haha,” ucap Manda.
Label “anak UIN” yang religius kadang menjadi beban psikologis. Apalagi ketika ekspresi diri mereka tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
Antara Bertahan dan Berdamai
Meski tidak pernah mencintai kampus ini, sebagian dari mereka mulai belajar berdamai. Bukan karena semuanya membaik, tapi karena mereka harus bertahan.
Manda mulai melihat sisi positif dari mengajar, meski awalnya tak pernah terbayang menjadi guru. Imam mencoba lebih dalam memahami sistem dan berjuang agar ilmu yang ia dapat tak sia-sia. Rani tetap percaya bahwa meski dunia memandang hukum Islam sebelah mata, dia punya ruang perjuangannya sendiri.
Suara dari Pinggir Sistem
Cerita-cerita mereka adalah suara-suara yang tak muncul di ruang orientasi, tak terdengar di meja birokrasi, dan tak dipedulikan dalam selebrasi kelulusan. Mereka tidak gagal. Mereka hanya datang dari jalur yang tidak ideal. Mereka tidak malas. Mereka hanya menjalani sesuatu yang tidak pernah benar-benar mereka pilih.
Kuliah, bagi mereka, bukan mimpi yang digapai. Tapi semacam kompromi yang dijalani. Dan itu tidak membuat mereka lebih rendah. Justru di tengah keterbatasan, mereka belajar bertahan. Dalam diam, mereka tumbuh.
“Bukan soal pilihan terbaik, tapi gimana bertahan di jalan yang udah kita lewati,” kata Imam.
“bagaimana lagi? Ini udah jalan yang dibukakan. Kita jalani aja sampai akhir,” tutup Manda.
Tulisan ini bukan untuk menyudutkan institusi. Ini adalah potret kecil dari sekian banyak mahasiswa yang datang dari latar belakang berbeda, membawa beban berbeda, dan punya kisah yang tak sempat diucap. Di antara tumpukan skripsi dan rapat organisasi, ada cerita-cerita yang hanya bisa dibaca lewat mata yang jujur.